Oleh Nik Abdul Rakib Bin Nik Hassan
Kali ini di
dalam bulan Randhan, saya ketengahkan artikel berfokus kepada islami dengan Tajuk
Sifat Kritis Dalam Tradisi Pemikiran Islam. Sebuah tulisan Dr. Azhar Ibrahim Alawee
dari National University of Singapore. Isi tulisannya ada seperti berikut:-
Tradisi humanistik (bersifat kemanusiaan) mempunyai kehadiran yang kuat
dalam tradisi pemikiran Islam klasik, baik dalam ranah teologi, falsafah,
etika, hukum dan sastera (adab).
Sebagai suatu
gaya pemikiran, humanisme kritis memberi penekanan kepada kesedaran manusia
akan kehidupannya, bertanggungjawab dan berperanan dalam kehidupannya, dengan
mengenal pasti akan kekuatan dan kelemahan masing-masing.
Dimensi sosial
Islam menjadi bahagian terpenting dalam idealisme humanistik, yakni manusia itu
sayugia dipupuk sempurna melalui pendidikan, dengan akur akan kedudukan akal
yang tinggi, dengan memikul tanggungjawab etika, selain mengangkat kebebasan
dan ketinggian kerohanian.
Menyelusuri
sejarah pemikiran Islam, kita akan menemui pelbagai perspektif tentang
pendidikan. Suatu aspek pemikiran yang akan kita ketemui ialah gaya pemikiran
yang humanistik dalam aliran pemikiran Islam yang mana idea dan perspektif
mereka tentang pendidikan dapat kita jejaki juga. Humanisme kritis pernah
berdenyut dalam tradisi Islam dan itulah yang wajar kita gali dan bangunkan
kembali.
Tarif Khalidi mentakrif humanisme sebagai “suatu sistem untuk mengkaji alam dan masyarakat yang… keluar dari pengkhususan yang sempit dan mendekati pendekatan yang diskusif dan berbilang dimensi, sanggup menyelidik segala fenomena alam dan sosial dalam semangat yang toleran dan skeptis".
Tarif Khalidi
seorang ahli sejarah Palestin yang kini memegang Kerusi Shaykh Zayid dalam
Pengajian Islam dan Arab di Universiti Amerika Beirut di Lubnan
Alija
Izetvigobic, seorang pemimpin Muslim dari Bosnia mentakrifkan humanisme sebagai
“asas afirmasi manusia dan kebebasannya, yakni nilainya sebagai manusia.”
Pastinya dalam
masyarakat Islam, humanisme atau sifat berperikemanusiaan difahami sebagai
humanisme agama dengan afirmasi Tauhid menjadi terasnya.
Humanisme
kritis dalam tradisi Islam menyuguhkan agama sebagai pusat dalam pencerahan
manusia dan masyarakat. Dalam rangka falsafah kritis, kewujudan manusia itu
adalah pencapaian sa’adah (kebahagiaan) yang memiliki nuansa pembebasan,
melawan kesengsaraan manusia dan melawan apa jua bentuk fikiran yang membungkam
kebebasan manusia berfikir dan nuraninya. Keadaan ini boleh tercapai melalui
pendidikan adab dan pelatihannya, serta pendedahan kepada hikmah dan falsafah. Malah
era yang disebut sebagai zaman Islam klasik di mana beberapa sarjana telah
menyebutnya sebagai periode reinasans (tempoh kelahiran semula) Islam, dan di
situlah tradisi humanisme Islam dalam manifestasinya yang terbaik terungkap.
Bagi Al-Jahiz,
tokoh humanis Islam zaman klasik yang terbilang beranggapan bahawa segalanya
itu yang diturunkan kepada kita sebagai warisan (turath) adalah bagi kita yang
terkemudian hari untuk memeriksa, menghargai dan memilihnya. Para humanis dalam
Islam klasik melihat ilmu pengetahuan, sains dan hikmah yang mereka warisi dari
umat yang terdahulu seperti Yunani, Parsi, dan India, sebagai satu
tanggungjawab Muslim untuk membangunkan lagi dan menghargainya.
Hari ini,
idealisme humanistik berdenyut dan terlafaz dalam kalangan Muslim reformis yang
mengajukan rekonstruksi (pembangunan semula) masyarakat Islam lewat ijtihad
dalam pemikiran keagamaan dan rombakan idea pendidikan.
Jelas sekali,
tradisi humanistik bukan sahaja menyuguhkan cita-cita muluk untuk manusia
sejagat tetapi juga ia harus ada kemahuan untuk mengadun semangat kreatif
dengan pemikiran kritis demi menyempurnakan tugas transformatif sebagai
khalifah di bumi ini.
Setem Syria
dengan wajah Al-Jahiz, dikeluarkan pada 1968.
Pengiktirafan Akal Manusia
Menarik
diperhatikan tradisi rasionalistik (fikiran yang berasaskan logik) dalam Islam
itu boleh dianggap sebagai gerbang utama untuk pemikiran humanistik terbangun
dalam peradaban Islam. Dalam tradisi falsafah Islam, keunggulan akal ditekankan
sambil menepis kegerunan ortodoks tentang bahaya dan kekurangan akal pada
manusia.
Diperingatkan
oleh Hayyan at-Tauhidi bahawa: “Segala tumpuan ilmu ataupun kesalihan tidak
akan cukup untuk membentuk watak yang baik dan soleh, melainkan dengan iradat
akal". Ibn Hazm dalam bukunya al-Muhalla berpendapat:
“Seorang
mujtahid itu yang berijtihad tetapi terbabas lebih baik dari seorang yang
mengikuti secara taqlid walaupun taqlid itu benar.”
Menuntut ilmu
dan menguasainya hanya akan bermakna sekiranya ia ada matlamat untuk memberi
bakti atau sumbangan kepada orang lain. Menuntut ilmu hanya semata-mata kerana
ingin menuntutnya telah dikritik seperti yang disebut al-Ghazali,
“Sekiranya
seorang itu membaca seratus ribu perihal ilmu dan mempelajarinya dengan tekun
tetapi tidak ia mengamalkannya, maka ilmu itu tidak berguna kepadanya kerana
kebesaran ilmu itu terletak apabila ia diamalkannya.”
Dalam zaman
Islam klasik, menuntut dan menimbangkan secara falsafah bertujuan untuk
“membangunkan roh, menguatkan akal, memperbaiki akhlak, menyemai amal dan
menjauhi kejahatan.”
Sepertimana
yang dinyatakan oleh Hayyan at-Tauhidi. Bagi ahli falsafah, ilmu mereka
dianggap sebagai “puncak matlamat dalam pendidikan humanistik dan asas kepada
segala ilmu yang boleh menyampaikan kepada kesempurnaan manusia serta mencapai
kebahagiaan dan jalan selamat".
Pemikiran Humanistik dalam Era Moden
Hari ini,
idealisme humanistik terungkap dalam kalangan reformis Muslim yang mengajukan
rekonstruksi masyarakat Islam dengan mengambil jalan kembali kepada ilmu
filsafat (falsafah), ilmu sains kemasyarakatan, ilmu pendidikan dan pedagogi,
selain pembaharuan dalam pemikiran keagamaan Muslim.
Inilah yang
dikatakan pemikiran Muslim zaman ini perlu disegarkan kembali dari tradisi
humanismenya, yang dalam peredaran zaman telah terbeku dan dilupakan. Ini dapat
kita lihat dalam pengajuan, pembaharuan yang dibawa oleh Jamaluddin al-Afghani
yang terkenal dengan pengajuannya supaya dihidupkan kembali semangat
berfalsafah, sedangkan anak didiknya mengikut jejak yang sama, yakni Sheikh
Muhammad Abduh, Syeikhul al-Azhar yang terkenal dengan idea pembaharuannya.
Jamaluddin
al-Afghani merupakan antara pemikir paling awal dalam era moden ini yang
memperhatikan perlunya golongan ilmuwan dalam kalangan masyarakat Islam yang
bersikap kritis dalam permasalahan pemikiran dan perbuatan mereka. Al-Afghani
menyifatkan kemunduran masyarakat Islam disebabkan oleh pembekuan pemikiran
dalam kalangan alim ulama, yang sepatutnya menjadi penjaga dan penentu
kehidupan intelektual masyarakat Islam.
Antara
pembekuan yang jelas adalah penolakan terhadap falsafah. Juga kepimpinan
intelektual dalam masyarakat Islam sudah membeku dan tertutup. Ulama
tradisionalis (pendukung fahaman, ajaran, dan lain-lain berdasarkan tradisi)
hanya mempedulikan ilmu agama, mereka telah mengabaikan cabang ilmu yang lain,
malah memandang sepi terhadap apa jua ilmu dunia yang bagi mereka tidak akan
menyampaikan ke jalan akhirat.
Tanggapan
seperti itu harus diperbetulkan dan itulah antara agenda pembaharu Islam, di
saat-saat umat Islam terbelenggu dalam kemunduran dan penjajahan.
Membangunkan
pemikiran Islam memerlukan sumbu ilmu yang membuana dan membumi. Tegas
Al-Afghani, semangat falsafah itu membenarkan kita “untuk membicarakan hal
ehwal umum tentang dunia dan keperluan manusia".
Semangat
berfalsafah merupakan satu upaya yang menyebabkan manusia menjurus kepada
penelitian, dan secara kritis, membelek-belek idea yang terlazim, menganalisis
secara mendalam kerumitan-kerumitan dalam masyarakat dan fenomena alam, dan
mencadangkan jalan keluar atau alternatif kepada permasalahan yang dihadapi
oleh manusia dan masyarakat.
Satu ruang
intelektual dan falsafah yang praktikal akan membolehkan pertukaran dan
perdebatan, langsung mengurangkan proses-proses simplifikasi dan desakan
pelbagai versi totalitarianisme dan kecenderungan harfiah.
Membangunkan
Humanisme Kritis dalam Pendidikan Islam
Humanisme
kritis adalah pemikiran kritis yang harus wujud dalam cakerawala pemikiran
kita. Ranah agama juga harus dihidupkan dengan humanisme kritis ini, selain ia
harus juga menyangkuti ranah-ranah pendidikan, kebudayaan, politik, dan
kemasyarakatan.
Maka para
humanis zaman ini seperti Mohamed Arkoun telah mengenal pasti pentingnya projek
memikir ulang tradisi Islam atas sebab dua keperluan: pertama masyarakat Muslim
harus memikirkan masalah mereka sendiri yang telah menjadi sesuatu yang tidak
terfikir disebabkan oleh lamanya pemikiran yang bersifat ortodoks.
Kedua,
perlunya pemikiran kontemporari untuk membuka ranah-ranah dan penemuan baharu
dalam dunia ilmu lewat pendekatan lintas budaya dan displin ilmu, sewaktu
berhadapan dengan masalah kehidupan sejagat.
Hari ini, para
reformis Muslim melihat dimensi humanistik sebagai batu asas yang penting dalam
kehidupan keagamaan, teristimewa pendidikan agamanya.
Merekonstruksikan
kembali idea dan visi pendidikan agama adalah sama pentingnya dengan mengajukan
perubahan pedagogi kurikulum.
Soedjatmoko,
seorang pemikir Indonesia yang terkenal, dengan tuntas menunjukkan betapa
pendidikan agama itu penting dalam pembangunan negara-bangsa seperti di
Indonesia kerana menurutnya:
(1) ia
berusaha ke arah pemupukan beberapa ciri seperti keberanian untuk hidup
mandiri, mengambil inisiatif, sensitif terhadap hak-hak orang lain dan
keperluan kolektif dalam masyarakat dan umat manusia, sanggup untuk bekerjasama
demi kebaikan umum dalam proses perubahan sosial, tanpa takut kepada perubahan
yang sedang berlaku;
(2) berusaha
ke arah memupuk motivasi yang kental pada anak didiknya untuk mempelajari dan
memahami realiti sosial yang terdapat dalam masyarakat;
(3) berusaha
ke arah merangsang para pelajar untuk mempraktikkan apa yang mereka yakini;
(4) berusaha
ke arah integrasi dan sinkronisasi (penyelarasan) dengan pendidikan yang bukan
daripada jurusan keagamaan.
Pendek kata,
apabila membicarakan pemikiran Islam bukan sahaja harus mengambil kira tradisi
keintelektualan Islam yang berbagai, tetapi melihat aliran humanistik yang
harus terbangun dalam sistem pendidikan Islam kontemporari.
Selagi kita
tidak dapat mengaitkan soal pemikiran Islam dengan keperluan dan cabaran
kemanusiaan dan kezamanan, kita sebenarnya telah memutuskan pemikiran dan
pendidikan Islam dari nadi kerelevanannya.
Untuk kita
membangunkan sebuah gagasan falsafah pendidikan Islam, kita harus mengambil
kira kondisi semasa dan setempat, selain menimbangkan struktur sosioekonomi
masyarakat masing-masing.
Memetik
tanggapan Nurcholish Madjid, seorang pemikir Islam asal Indonesia, yang tekun
mengajukan gagasan kemanusiaan Islam, wajar kita menimbangkan bersama:
“Kerja
kemanusiaan atau amal soleh itu merupakan proses perkembangan yang permanen.
Perjuangan kemanusiaan berusaha agar perubahan dan perkembangan dalam
masyarakat selalu mengarah kepada yang lebih baik, lebih benar. Oleh sebab itu,
manusia harus mengetahui arah yang benar daripada perkembangan peradaban di
segala bidang."
"Dengan
perkataan lain, manusia harus mendalami dan selalu mempergunakan ilmu
pengetahuan. Kerja manusia dan kerja kemanusiaan tanpa ilmu tidak akan mencapai
tujuannya, sebaliknya ilmu tanpa rasa kemanusiaan tidak akan membawa
kebahagiaan bahkan mungkin menghancurkan peradaban.”
Di sinilah
humanisme kritis boleh menyumbang. Membicarakan aspek-aspek humanisme kritis
yang terlafaz dalam tradisi pemikiran Islam dari zaman sebelumnya, harus dapat
memacu kita untuk membangunkan pemikiran Islam yang moden, progresif dan
humanistik.
Itulah antara tugas umat Islam untuk benar- benar berdiri atas keyakinan bahawa Islam sebagai rahmatan lil alamin. Dan kitalah yang bersaksi dan bertindak ke arah itu, demi kesejahteraan umat manusia dalam alam ini. Inilah yang tertanggung ke atas kita hari ini.

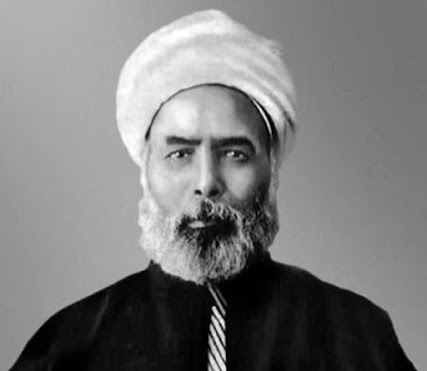


Tiada ulasan:
Catat Ulasan